Daftar Isi ⇅
show
osiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan (Damono dalam Wiyatmi, 2013, hlm. 5). Seperti namanya, sosiologi sastra adalah upaya untuk memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Dalam wacana ini, sastra berdiri sebagai fenomena masyarakat yang ditelaah dalam kacamata ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosiologi.
Sosiologi sastra, yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial, merupakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan sosiologi. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan hakikat sosiologi sastra menurut Swingewood (dalam Wiyatmi, 2013, hlm. 6), kita harus terlebih dulu mengetahui batasan sosiologi sebagai sebuah ilmu dan menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dengan sastra.
Swingewood (dalam Wiyatmi, 2013, hlm. 6) mengungkapkan bahwa sosiologi adalah studi ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat serta lembaga-lembaga dan proses sosialnya. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup.
Baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Keduanya berusaha memahami hubungan antarmanusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat.
Bedanya, sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, lembaga dan proses sosial—mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, bagaimana ia tetap ada; sementara itu sastra menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya dan melakukan telaah subjektif dan personal (Damono dalam Wiyatmi, 2013, hlm. 7).
Definisi yang lebih mutakhir juga menegaskan peran sosiologi sastra sebagai representasi masyarakat: Ahmadi (2021) menyebut bahwa sastra adalah bagian dari sistem sosial suatu zaman, dan bahwa analisis sosiologi sastra tidak bisa dilepaskan dari institusi dan kelompok sosial yang membentuk latar sosial teks tersebut.
Lebih lanjut, studi oleh Jurnal Bastra (2022) tentang teks religius menunjukkan bahwa teks sastra memiliki elemen intrinsik (tata bahasa, gaya, struktur) dan ekstrinsik (konteks historis, sosial, budaya) yang saling mempengaruhi; konteks sosial-historis sangat menentukan bagaimana teks terbentuk dan dipahami.
Dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah pendekatan yang mengkaji, memahami, hingga menilai karya sastra dengan menggunakan studi sosiologi yang menelaah manusia, masyarakat, lembaga sosial, konteks historis, serta struktur sosial yang menaunginya.
Pendekatan Sosiologi Sastra
Santosa dan Wahyuningtyas (2011, hlm. 24) menyatakan, karya sastra itu unik karena merupakan perpaduan antara imajinasi pengarang dengan kehidupan sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakatnya karena masalah yang dilukiskan dalam karya sastra merupakan masalah-masalah yang ada di lingkungan kehidupan pengarangnya sebagai anggota masyarakat. Di sinilah keduanya bertemu kembali dan menyiratkan bahwa harus terjadi interaksi interdisiplin dalam mengkaji suatu karya sastra.
Lantas sebetulnya bagaimana pendekatan sosiologi sastra dalam mengkaji karya sastra? Terdapat tiga pendekatan yang umumnya dilakukan, yakni sosiologi pengarang, karya sastra, dan pembaca. Ketiga tipe sosiologi sastra tersebut dikemukakan oleh Wellek dan Warren dalam bukunya Theory of Literature (1994, hlm. 109-133). Berikut adalah penjelasan dari ketiga pendekatan sosiologi sastra yang dapat digunakan untuk mengkaji sastra.
Sosiologi Pengarang
Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Dapat dikatakan bahwa sosiologi pengarang adalah kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra (Wiyatmi, 2013, hlm. 29).
Dalam sosiologi pengarang, pengarang sebagai pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat, ideologi yang dianutnya, posisinya dalam masyarakat, juga hubungannya dengan pembaca. Dalam penciptaan karya sastra, campur tangan penulis sangat menentukan, karena realitas yang digambarkan dalam karya sastra ditentukan oleh pikiran penulisnya (Caute dalam Junus, 1986, hlm. 8).
Meskipun begitu, realitas yang digambarkan dalam karya sastra sering kali bukanlah realitas apa adanya, tetapi realitas seperti yang diidealkan pengarang. Tidak heran jika beberapa karya sastra mencampuradukkan realitas dan imajinasi pengarang di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karya sastra melalui sosiologi pengarang membutuhkan data dan interpretasi sejumlah hal yang berhubungan dengan pengarang.
Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain adalah meliputi:
- status sosial pengarang,
- ideologi sosial pengarang,
- latar belakang sosial budaya pengarang,
- posisi sosial pengarang dalam masyarakat,
- masyarakat pembaca yang dituju,
- mata pencaharian sastrawan (dasar ekonomi produksi sastra),
- profesionalisme dalam kepengarangan.
Semua hal yang berkaitan dengan pengarang tersebut akan berpengaruh langsung pada karya sastra yang dibuatnya. Misalnya, status sosial pengarang yang tinggi akan memberikan berbagai perspektif yang berbeda dengan penulis yang berada di status sosial rendah. Kacamata keduanya akan berbeda jauh bak orang yang melihat dari atas ke bawah, dan orang yang melihat dari bawah ke atas. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap latar belakang pengarang untuk mengkaji lebih jauh mengenai karya sastra yang ditelurkannya.
Sosiologi Karya Sastra
Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat (Wiyatmi, 2013, hlm. 45). Sosiologi sastra ini berangkat dari teori mimesis Plato, yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan.
Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial (Wellek dan Warren, 1994 dalam Wiyatmi, 2013, hlm. 45). Sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat.
Beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra meliputi:
- isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial;
- mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat atau bias realita dari kenyataan; dan
- mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosiobudaya suatu masyarakat pada masa tertentu (Junus, 1986).
Sosiologi Pembaca
Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca (Wiyatmi, 2013, hlm. 60). Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain adalah:
- permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra,
- sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial,
- perubahan dan perkembangan sosial (Wellek dan Warren, 1994 dalam Wiyatmi, 2013, hlm. 60).
Sosiologi pembaca juga mengkaji fungsi sosial sastra, mengkaji sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial.
Pembaca
Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya. Dalam hubungannya dengan masyarakat pembaca atau publiknya, menurut Wellek dan Warren (1994), seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publiknya atau pelindungnya, tetapi juga dapat menciptakan publiknya. Menurutnya, banyak sastrawan yang melakukan hal tersebut, misalnya penyair Coleridge. Sastrawan baru, harus menciptakan cita rasa baru untuk dinikmati oleh publiknya.
Perlu dilakukan kajian secara empiris mengenai siapa sajakah pembaca yang secara nyata (riel) membaca karya-karya pengarang tertentu. Apa motivasinya membaca karya tersebut? Apakah mereka membaca karena ingin menikmatinya sebagai sebuah karya seni? Membaca karena harus melakukan penelitian terhadap karya-karya tersebut? Atau membaca karena harus memilih karya-karya tertentu untuk berbagai kepentingan khusus?
Perlu diteliti juga bagaimana para pembaca tersebut menilai dan menanggapi karya sastra yang telah dibacanya? Faktor-faktor apa sajakah (secara sosiologis dan psikologis) yang berpengaruh dalam menilai dan menanggapi karya sastranya?
Dampak dan Fungsi Sosial Karya Sastra
Setelah sampai pada pembacanya, karya sastra akan dibaca, dihayati, dan dinikmati pembaca dan memberikan dampak serta fungsi sosial pada pembaca dan orang-orang di sekelilingnya (masyakat). Dalam hubungannya dengan fungsi sosial sastra, Ian Watt (dalam Damono, 1979) membedakan adanya tiga pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu:
- pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak;
- pandangan “seni untuk seni”, yang melihat sastra sebagai penghibur belaka; dan
- bersifat kompromis, di satu sisi sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur.
Untuk menerapkan kajian ini terlebih dulu perlu ditentukan wilayah kajiannya, misalnya apakah akan membatasi pada komunitas pembaca tertentu yang membaca dan menanggapi karya tertentu, atau akan meneliti juga bagaimana karya tertentu ditanggapi oleh pembacanya?
Faktor-faktor sosial budaya politik apa yang melatarbelakangi tanggapan pembaca, atau bagaimanakah pembaca memanfaatkan karya tertentu? Setelah menentukan wilayah kajiannya, selanjutnya kumpulkanlah data yang diperlukan, dilanjutkan dengan memaknai data tersebut.
Pendekatan Sosiologi Sastra Mutakhir dari Penelitian Terbaru
Untuk melengkapi pendekatan klasik di atas, studi-terbaru menunjukkan beberapa perkembangan sebagai berikut.
Fatmawati, Dessy Wardiah, & Arif Ardiansyah (2023) menggunakan pendekatan pengarang, karya, dan pembaca sekaligus dalam analisis novel Dibalik Rahasia Senja, dengan menelusuri bagaimana konteks sosial pengarang dan budaya masyarakat terlihat dalam karya, serta dampak sosial karya tersebut terhadap pembaca.
- Nur Maulidya (2022) dalam Analisis Novel Belenggu melihat bagaimana modernisasi dan tradisi berkonflik dalam karya sastra, yang menunjukkan bahwa karya sastra tidak hanya pasif mencerminkan masyarakat tetapi juga merespons perubahan sosial.
- Penelitian Masalah Sosial dalam Novel Penyalin Cahaya (Pramesthi, Sutanto & Waslam, 2023) menyoroti bahwa aspek seperti ekonomi, generasi muda, norma sosial, dan birokrasi adalah bagian nyata dari pendekatan sosiologi sastra karya sastra dan hubungan pembaca karya sastra.
Bacaan Lebih Lanjut
Setelah tiga pendekatan utama yang biasa digunakan dalam kajian sosiologi sastra, terdapat beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan sebagai pisau analisis pendekatan ini. Beberapa teori tersebut meliputi: sosiologi sastra marxis, strukturalisme genetik, dan teori hegemoni Gramsci dalam kajian sosiologi sastra. Beberapa pendekatan sosiologi sastra tersebut akan dibahas dalam artikel terpisah di lain kesempatan karena membutuhkan uraian dan pemaparan yang tidak sedikit.
Referensi
- Ahmadi, R. (2021). Sociology of literature. International Journal of Advanced Academic Studies, 3(1), 129–133. https://doi.org/10.33545/27068919.2021.v3.i1b.480
- Damono, Sapardi Djoko. (1979). Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Singkat. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Fatmawati, F., Dessy Wardiah, & Arif Ardiansyah. (2023). Analisis sosiologi sastra dalam novel Dibalik Rahasia Senja karya Wahyu Sujani. Pembahsi (Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia), 13(2), 125-138. https://doi.org/10.31851/pembahsi.v13i2.12587
- Hasanah, A. A. (2022). Sociology of Literature as Approach in the Study of Religious Texts. Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 7(2), 286–297. https://doi.org/10.36709/bastra.v7i2.80
- Junus, Umar. (1986). Sosiologi Sastra: Persoalan Teori dan Metode. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Maulidya, N. (2022). Analisis sosiologi sastra terhadap gambaran kontradiksi dan modernisasi dalam novel Belenggu karya Armijn Pane. Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra, 9(2), 155-165. https://doi.org/10.30595/mtf.v9i2.15104
- Pramesthi, E. A., Sutanto, E., & Waslam. (2023). Masalah sosial dalam novel Penyalin Cahaya karya Lucia Priandarini: pendekatan sosiologi sastra. Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 8(2), 226-236. https://doi.org/10.36709/bastra.v8i2.174
- Santosa, Heru Wijaya dan Sri Wahyuningtyas. (2011). Sastra: Teori dan Implementasi. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Wiyatmi. (2013). Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
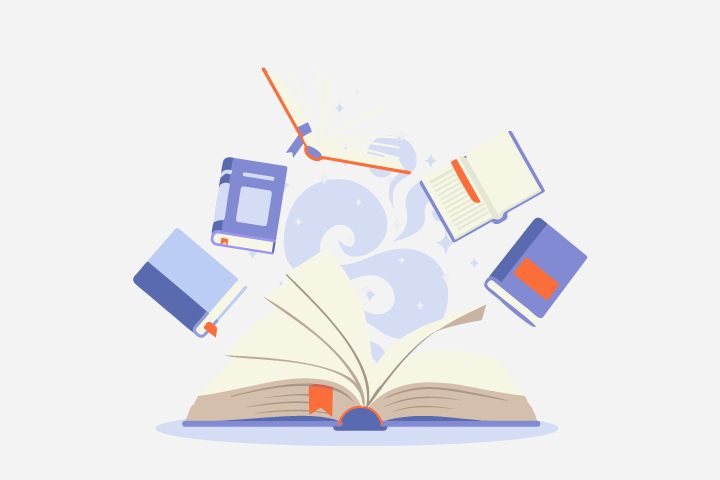
Sipdah artikelnya